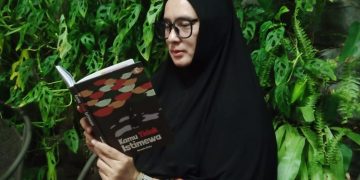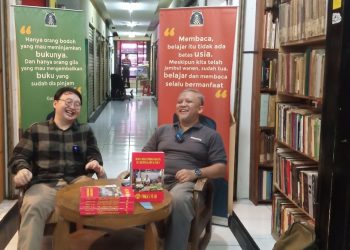Oleh Lydia Longlei (Mahasiswa STIPAS St. Sirilus Ruteng)
Suaranusantara.co –Pada awal tahun 2020 dunia dikejutkan dengan wabah virus corona (covid-19) yang menjangkiti manusia di hampir semua belahan dunia. Tercatat, virus ini diakui dunia tatkala pada 11 Maret 2020, World Health Organization (WHO), resmi mengumumkan kejadian luar biasa virus corona atau Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) sebagai pandemi global. Hingga 31 Mei 2021 lalu, virus tersebut telah tersebar dengan pesat setidaknya di 219 negara atau teritori, dengan total infeksi global lebih dari 171,5 juta kasus dan 3,7 juta kematian. Tingginya kecepatan penyebaran wabah ini memberikan dampak negatif yang luar biasa yang besar bagi seluruh negara, baik dari sisi kesehatan, sosial dan kesejahteraan, maupun ekonomi (Ghebreyesus, 2021:14).
Kehadiran virus tersebut telah merubah hidup manusia di abad-21. Kehadirannya merubah seluruh dimensi kehidupan. Dia menjadi ancaman bagi keberlangsungan hidup manusia di abad ini. Kehadirannya membuat manusia hidup dalam kecemasan dan menderita berkepanjangan. Demi melindungi diri, manusia terpaksa harus membatasi aktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari. Kehadiran virus ini, telah membuat masyarakat harus membatasi segala aktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan pekerjaan yang menjadi kebiasaan sehari-hari terpaksa tidak dilakukan. Tidak hanya itu, bahkan masyarakat juga dilarang untuk berkumpul, dilarang untuk keluar rumah tanpa menggunakan masker, dan juga dilarang melakukan kontak fisik dengan orang baru.
Pandemi Hoaks
Di tengah penyebaran Covid-19, dunia dan masyarakat kita juga harus menghadapi pandemi hoaks. Pandemi ini semakin meningkat seiring perkembangan dunia digital yang semakin canggih. Hoaks adalah berita atau informasi palsu yang menyebarluas di tengah kehidupan masyarakat yang secara sengaja dibuat oleh seorang atau kelompok tertentu untuk mempengaruhi orang lain demi kepentingannya. Hoaks dapat diartikan sebagai informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi yang sebenarnya, atau informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Hoaks diidentikkan sebagai berita bohong, yaitu berita yang jauh dari kenyataan sebenarnya. Hoaks dapat terjadi karena rendahnya literasi. Dalam kondisi seperti itu sebuah informasi dibesar-besarkan seakan-akan berita tersebut fakta (Anggraini, 2021:2).
Penyerbaran hoaks begitu berbahaya. Salah satu penelitian yang menunjukkan tingkat keberbahayaan hoaks adalah yang dilakukan oleh Heidi Tworwk. Penelitian tersebut ditulisnya dalam artikel berjudul How Public Health Approach Could Help Curb The Infodemi. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa seiring dengan merebaknya Coronavirus Disease (Covid-19) sejak tahun 2020 lalu ditemukan ada 800 orang di seluruh dunia mengalami kematian gara-gara membaca informasi online yang mengatakan; “dengan mengonsumsi alkohol konsentrasi tinggi maka membuat orang terlindungi dari ketularan Covid-19”. Informasi ini membawa kematian bagi orang-orang tersebut karena mereka percaya dan melakukannya (minum alkohol dalam kadar dan konsentrasi tinggi). Kematian sia-sia tersebut seharusnya tidak perlu terjadi jika informasi yang dipublikasikan adalah informasi yang benar dan akurat, atau sekurang-kurangnya mereka yang membaca tidak membenarkan begitu saja informasi tersebut.
Di Indonesia, fenomena penyebaran berita palsu melalui saluran digital amat jamak terjadi dan menjadi tantangan yang tidak ringan. Dalam survei Edelman Trust 2022 yang dirilis Januari lalu, terlihat bahwa Indonesia menempati urutan kedua terkait kecemasan publik terhadap berita bohong, yaitu berada di angka 83 persen (Kompas, Rabu 9 Februari 2022). Hal ini diperparah dengan fenomena jurnalisme rendahan, di mana terdapat fenomena mengejar klik (clickbait) dengan membuat judul-judul berita yang menggoda, namun melenceng dari makna.
Kultur Literasi
Eko Nugroho (2021:24) menguraikan beberapa langkah sederhana namun penting yang bisa membantu dalam mengidentifikasi hoaks. Pertama, berhati-hati dengan judul berita provokatif dan sensasional. Kedua, membiasakan diri untuk memeriksa dan memverifikasi fakta. Ketiga, berpartisipasi dalam grup-grup diskusi anti hoaks. Langkah-langkah kecil tersebut amat penting agar terbebas dari manipulasi data atau informasi yang sering dijadikan modus dalam penyebaran informasi dalam era komunikasi digital sekarang ini.
Namun, langkah-langkah yang disebutkan di atas memerlukan satu fundasi yang penting melalui kultur literasi. Sebab salah satu senjata paling ampuh untuk mengatasi hoaks adalah dengan meningkatkan kultur literasi. Dengan kultur yang kuat, maka akan komunitas masyarakat yang berpikir rasional, kritis dan inovatif, berwawasan luas dan konstruktif, serta dapat mencegah diri dari reaksi-reaksi yang bersifat emosional atas informasi atau peristiwa.