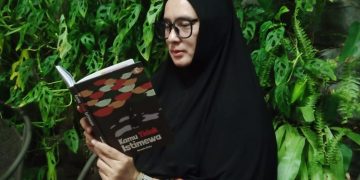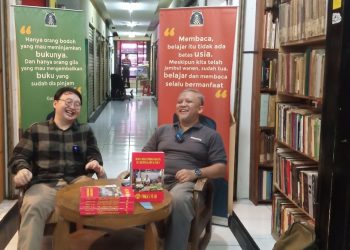Jakarta, Suaranusantara.co – Investasi paling kokoh dalam kehidupan adalah investasi akademis dan SDM (Sumber Daya Manusia). Uang bisa di ambil orang, tetapi metodologi untuk memperolehnya, orang tidak bisa mengambilnya. Metodologi itulah yang penulis maksud dengan kekayaan intelektual (melalui skill dan kualitas diri).
Peradaban dunia merupakan sebuah produk perkembangan akal budi dan pengetahuan. Demikian pun halnya peradaban bangsa Indonesia lahir dari kematangan intelektualitas. Kita semua mengetahui, teknologi adalah anak kandung dari ilmu pengetahuan.
Dalam kaitannya dengan pendidikan nasional, kita mempunyai fondasi yang kuat, yaitu Pembukaan UUD 1945 memuat bahwa tujuan dibentuknya pemerintah negara Indonesia adalah untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa” dan pasal 31 UUD 1945 ayat 1 “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan ayat 2 “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.
Investasi di Indonesia
Di sinyalir bahwa, Relawan Jurnal Indonesia (RJI) memberi sumbangsih besar bagi Publikasi Ilmiah (PI) di Indonesia. RJI yang di mulai di Yogyakarta ini memproduksi akses pengetahuan yang berguna bagi setiap generasi. Konteks perkembangan open access yang membuka peluang bagi siapa saja yang ingin mengakses pengetahuan muncul seiring dengan perkembangan internet.
Hal ini pun didukung oleh Peraturan Kepala LIPI No. 3 tahun 2014 dan Dirjen Dikti No. 1 tahun 2014 tentang akreditasi terbitan berkala ilmiah. Perka tersebut menemukan sebuah solusi bahwa jurnal yang akan terakreditasi mulai tahun 2014 harus terbit dalam bentuk elektronik.
Relawan Jurnal Indonesia (RJI) hadir atas inisiatif pengelola jurnal di Yogyakarta dan di daerah lainnya seperti Bandung, Makassar, Sumatera Selatan dan Jawa Timur. RIJ adalah sebuah gerakan suka rela memberikan sumbangsih tenaga dan pikiran terkait pengelolaan jurnal elektronik. Kita melihat ada pergeseran dari jurnal cetak ke jurnal elektronik.
Realitas yang di alami
Indonesia di kategorikan sebagai pemakai internet terbesar di dunia di satu sisi. Di sisi lain, Indonesia sebagai negara indeks membaca terendah di dunia. Ada dua hal yang sangat kontradiktif. Ini menjadi keprihatinan bersama, baik tingkat pribadi, sosial, maupun pemerintah.
Kedua ketegangan tersebut merupakan “peluang sekaligus tantangan” bagi Indonesia. Indonesia harus melihat itu sebagai peluang. Rendahnya minat baca masyarakat Indonesia juga dikuatkan oleh sebuah studi yang dilakukan Central Connecticut State University pada tahun 2016 mengenai ”Most Literate Nations in The World“.
Studi tersebut menghasilkan Indonesia menempati urutan ke-60 dari total 61 negara, atau dengan kata lain minat baca masyarakat Indonesia 0,01 persen atau satu berbanding sepuluh ribu. Ironinya, angka ini berbanding terbalik dengan jumlah pengguna internet yang mencapai separuh dari total populasi penduduk Indonesia atau sekitar Rp 132,7 juta.
Rendahnya minat baca di Indonesia, menurutt Colin McElwee, Co-Founder World reader, salah satunya dipengaruhi oleh sulitnya akses terhadap buku. Hemat penulis, bukan di situ duduk perkaranya. Berbagai hasil survey menunjukkan bahwa minat baca di Indonesia sangat rendah. Duduk perkaranya adalah harus melihat dari keseluruhan. Faktor paling tinggi, hemat penulis adalah niat.
Hal yang serupa pada tahun 2015, Perpustakaan Nasional, merilis bahwa hanya 10% dari masyarakat Indonesia yang berusia di atas 10 tahun yang gemar membaca. Pertanyaannya adalah apakah kegemaran membaca buku untuk saat ini dapat merefleksikan minat baca secara menyeluruh? Yang perlu diperbaiki adalah metode pembelajaran. Sistem menghafal sudah menjadi bagian utuh dalam sistem pendidikan di Indonesia. Tidak salah juga kalau menggunakan metode menghafal. Hanya saja metode menghafal melahirkan generasi kurang kreatif dan inovatif. Generasi yang hidup dalam zona nyaman dan merasa sudah cukup dengan pengetahuan yang telah dihafal.
Dalam pengamatan penulis, mata pelajaran di tingkat SD, SMP dan SMA terlampau banyak. Siswa menguasai “banyak hal” dan mendalami “sedikit hal”. Sedangkan, Eropa dan negara maju lainnya mempelajari “sedikit hal” dan mendalami atau mengetahui “banyak hal”.
Kehadiran Relawan Jurnal Indonesia (RJI) menjadi sebuah momen emas bagi perkembangan publikasi ilmiah melalui jalur OJS (Open Journal System). Kehadiran RJI patut di sambut meriah. Namun, RJI juga harus menghadapi ambang peluang atau tantangan.
Peluang Investasi
Menteri Pendidikan sudah menerapkan kebijakan pendidikan yang bagus,. Yaitu kelulusan di tentukan oleh sekolah. Dengan demikian, penilaian tidak saja menerapkan aspek intelektual, tetapi juga aspek kepribadian dan emosional.
Indonesia masih asing dengan pelajaran filsafat. Kegunaan pelajaran filsafat adalah untuk menyaring kebenaran. Menurut Socrates, ada tiga saringan utama ketika seseorang membicarakan sesuatu. Pertama, apakah yang dibicarakan benar. Kedua, apakah yang dibicarakan adalah hal yang baik. Dan, saringan ketiga adalah kebermanfaatan. Ketiga hal tersebut merupakan tes saringan pengetahuan.
Indonesia selalu memproduksi gosip (gibah). Orang Indonesia selalu menerima kebenaran tanpa saringan. Sehingga, banyak media memproduksi “hoaks”.
Dengan adanya open access memberi peluang bagi masyarakat untuk mengakses pengetahuan yang orisinil dan akurat. Tulisan di jurnalnya umumnya akurat karena sudah melewati proses editing. Peluang ini pun berlaku bagi negara untuk meningkatkan minta membaca.
Tantangan Investasi
Di era revolusi 4.0 di tandai dengan era internet. Sedangkan di beberapa tempat lain, di pelosok Indonesia, jangankan internet, listrik saja belum masuk. Sehingga, era revolusi 1.0 saja mereka belum merasakan. Bandingkan wilayah tertinggal Kalimantan, NTT dan Papua.
Penulis baru saja mendapat laporan dari seorang sahabat di Manggarai Timur, Flores, NTT. Dia adalah seorang guru. Namanya Fenansius Darmin Faman. Di sekolahnya, belum ada saluran PLN. Ini sebuah kisah dari pelosok negeri. Bagaimana kita membicarakan open access atau OJS, sedangkan mereka saja masih jauh dari kejayaan fasilitas.
Berbicara tentang journal online kini mendapat sebuah tantangan. Masih banyak tempat di negeri ini yang de facto, masih hidup di era revolusi 1.0 atau bahkan belum. Karena era revolusi 1.0 di tandai dengan adanya listrik. Di Papua, banyak tempat yang belum tersalur aliran listrik. Menyedihkan, bukan?
Fungsi Pendidikan
Penulis perlu memperlihatkan kembali fungsi pendidikan yang di impikan UNESCO, 2019. Menurut UNESCO terdapat 4As yang di kembangkan oleh mantan UN Special Rappotuer on the Right to Education, Katarina Tomasevki/ Ia menilai bahwa pendidikan dalam konteks sebuah hukum nasional, sebagai berikut.
Pertama, availability yang dapat di artikan bahwa pendidikan itu di danai oleh pemerintah, bersifat universal, gratis dan di wajibkan. Lebih jauh ini berarti tersedianya infrastruktur dan fasilitas yang memadai serta para pendidik yang bisa di andalkan.
Kedua, accessibility, di mana semua peserta didik mendapatkan akses yang sama terkait dengan pelayanan pendidikan terlepas dari gender, ras, agama, etnisitas atau pun status sosial-ekonomi. Di dalamnya juga termasuk fasilitas-fasilitas pendidikan harus tersedia dalam jarak yang relatif terjangkau dan berada di dalam komunitas.
Ketiga, acceptability, kualitas pendidikan yang di sediakan harus bebas dari diskriminasi dan sesuai dengan peserta didik. Di dalamnya termasuk jaminan metode pengajaran yang objektif dan tidak bias serta materi pembelajaran juga merefleksikan keyakinan-keyakinan yang luas. Hal ini juga berarti profesionalitas dari pendidik haruslah selalu di jaga.
Keempat, adaptability, merujuk pada program-program pendidikan haruslah cukup fleksibel, dapat di sesuaikan dengan perubahan sosial dan kebutuhan dalam komunitas tertent. Serta juga menampung keunikan dari peserta didik.
Dari keseluruhan uraian di atas, penulis merasa bahwa realitas Relawan Jurnal Indonesia antara peluang atau tantangan. Mari kita mengubah tantangan menjadi peluang.
Penulis: Eugen Sardono-Mahasiswa Program Magister Filsafat di STFT Widya Sasana, Malang – Relawan Jurnal Indonesia: Investasi di Ambang Peluang atau Tantangan